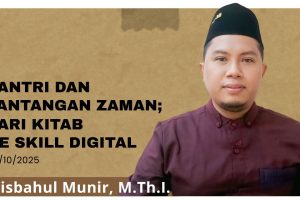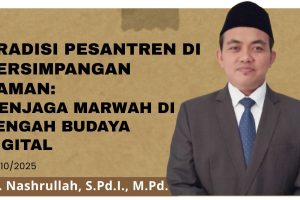Tantangan Keadilan Gender di Indonesia: Peran Strategis Pesantren
- Categories Kolom
- Date 19 May 2025
Oleh : Misbahul Munir, M. Th.I.
(Dosen UNKAFA Gresik, saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktoral dalam Progran Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI) kerjasama LPDP, Masjid Istiqlal dan Universitas PTIQ Jakarta)
Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemuliaan manusia idealnya menjadi pendorong utama dalam memperjuangkan keadilan ini. Sayangnya, dalam praktiknya, ajaran agama kerap disalahgunakan untuk membenarkan subordinasi perempuan. Akibatnya, perjuangan perempuan tidak hanya berhadapan dengan sistem sosial yang patriarkal, tetapi juga dengan tafsir keagamaan yang bias gender.
Namun demikian, kita juga melihat tumbuhnya semangat baru di tengah masyarakat—terutama di kalangan pesantren, lembaga pendidikan Islam, dan ulama perempuan. Mereka mulai membaca ulang ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih adil dan kontekstual. Mereka menyadari bahwa keadilan gender bukan ancaman bagi agama, tetapi justru merupakan bagian dari substansi Islam itu sendiri.
Ketimpangan yang Masih Mengakar
Ketimpangan gender di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam budaya patriarki. Dalam struktur sosial kita, laki-laki sering diposisikan sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama, sementara perempuan dibatasi dalam peran domestik. Pandangan seperti ini bukan hanya hadir dalam budaya lokal, tetapi juga menyusup ke dalam pemahaman agama yang dikonstruksi secara turun-temurun.
Salah satu wujud dari ketimpangan ini adalah rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan di berbagai daerah, terutama wilayah pedesaan. Banyak keluarga masih menganggap pendidikan untuk anak perempuan tidak sepenting anak laki-laki. Perempuan dianggap akan berakhir di dapur dan rumah tangga, sehingga tak perlu sekolah tinggi. Padahal, pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan.
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah terbatasnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi dan mental. Kesehatan yang tidak terjaga berdampak pada rendahnya produktivitas dan keterlibatan perempuan di sektor sosial dan ekonomi. Lebih dari itu, banyak perempuan mengalami kekerasan berbasis gender baik di ranah publik maupun privat, namun enggan melapor karena takut distigma atau tidak mendapat dukungan.
Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa norma sosial yang membatasi perempuan masih menjadi faktor kuat yang menahan laju kemajuan mereka. Di dunia kerja, misalnya, perempuan sering dianggap tidak layak menduduki posisi strategis karena dinilai “lemah”, “emosional”, atau tidak mampu memimpin. Sementara dalam politik, partisipasi perempuan masih rendah karena sistem elektoral dan struktur partai yang belum sepenuhnya inklusif.
Kenyataan ini menegaskan bahwa perjuangan keadilan gender bukan sekadar wacana normatif, melainkan perjuangan struktural yang membutuhkan perubahan paradigma—mulai dari rumah tangga, sekolah, tempat ibadah, hingga ruang kebijakan publik.
Organisasi Perempuan dan Tafsir yang Membebaskan
Dalam konteks keislaman, tantangan terbesar dalam perjuangan keadilan gender adalah penafsiran agama yang kaku dan konservatif. Banyak ajaran Islam sejatinya bersifat adil dan setara, namun dalam penafsirannya kerap digunakan untuk membenarkan ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan.
Tafsir klasik terhadap ayat-ayat seperti QS An-Nisa (4:34) dan QS Al-Ahzab (33:33) telah berulang kali digunakan untuk mengukuhkan struktur patriarki. Beberapa kitab tafsir menjelaskan istilah qawwamun (pemimpin) sebagai dasar supremasi laki-laki dalam rumah tangga, serta membolehkan pemukulan terhadap istri (daraba) sebagai bentuk kedisiplinan. Tafsir semcam ini juga menekankan pembatasan ruang gerak perempuan di ruang publik dan justifikasi poligami tanpa penekanan pada prinsip keadilan. Penafsiran seperti ini, meski historis, masih sering digunakan untuk membenarkan ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan di masa kini.
Menjawab tantangan tersebut, muncul gerakan reinterpretasi yang dikenal sebagai feminisme Islam. Pendekatan ini tidak menolak agama, tetapi mengajukan pembacaan ulang yang kontekstual dan berkeadilan. Salah satu tokoh penting dalam gerakan ini adalah Nasaruddin Umar, yang melalui karyanya Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (2010) menyatakan bahwa banyak ketimpangan gender bersumber dari cara pandang patriarkal dalam penafsiran, bukan dari teks Al-Qur’an itu sendiri. Ia mengusulkan pendekatan tematik dan hermeneutika dalam memahami ayat-ayat gender, serta menyoroti tokoh perempuan dalam Al-Qur’an seperti Maryam, Asiyah, dan Ratu Bilqis sebagai contoh kepemimpinan dan keberanian perempuan.
Lebih jauh, muncul pendekatan yang lebih operasional dan aplikatif dalam konteks Indonesia, yaitu Qira’ah Mubadalah yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Pendekatan ini menawarkan cara pembacaan teks agama dengan prinsip kesalingan (mubadalah) antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, dalam menafsirkan QS An-Nisa (4:3) tentang poligami, pendekatan ini menekankan keadilan sebagai syarat mutlak. Bahkan, jika tidak mampu adil, maka cukup satu istri sebagaimana ditegaskan oleh Al-Qur’an. Perspektif ini tidak menolak eksistensi poligami secara mutlak, tetapi mengkritisi penggunaannya yang sering abai terhadap prinsip moral dan kemanusiaan.
Qira’ah Mubadalah memperluas cakrawala tafsir dengan menghadirkan ayat-ayat ke dalam realitas sosial modern yang menjunjung prinsip rahmah, keadilan, dan kemanusiaan universal. Pendekatan ini menantang hegemoni tafsir patriarkal dan menawarkan narasi baru yang menyetarakan peran laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan.
Upaya reinterpretasi ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh individual, tetapi juga diperkuat oleh organisasi keagamaan progresif seperti Rahima, Fahmina Institute, dan terutama KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia). Mereka bukan hanya memproduksi tafsir alternatif, tetapi juga menyebarkannya secara sistematis melalui pelatihan, modul pendidikan pesantren, dan kampanye komunitas. KUPI bahkan mengeluarkan fatwa pelarangan kekerasan dalam rumah tangga, menunjukkan bahwa agama dapat digunakan sebagai sumber perlindungan dan pembebasan, bukan penindasan.
Organisasi-organisasi ini juga sangat piawai dalam mengadaptasi simbol dan bahasa lokal. KUPI, misalnya, menggunakan istilah “ulama perempuan” sebagai upaya untuk menegaskan otoritas perempuan dalam wacana keagamaan. Ini merupakan langkah strategis dalam membangun otoritas moral alternatif dari dalam tradisi Islam itu sendiri—sebuah pendekatan yang lebih efektif daripada konfrontasi langsung dengan arus konservatif.
Tentu saja, gerakan ini menghadapi resistensi dari kelompok konservatif yang mempertahankan tafsir literal. Resistensi itu justru mempertegas perlunya penguatan literasi agama progresif, khususnya di pesantren dan komunitas akar rumput. Literasi tafsir yang ramah gender mampu membuka jalan bagi santri dan masyarakat untuk memahami Islam sebagai agama pembebasan.
Dengan pendekatan seperti ini, tafsir agama tidak lagi menjadi tembok yang membatasi perempuan, melainkan jendela pembebasan. Tafsir bukan untuk mempertahankan dominasi, melainkan untuk menghadirkan maslahat. Inilah esensi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin—yang tidak hanya dirasakan oleh laki-laki, tetapi juga perempuan, anak-anak, dan seluruh lapisan masyarakat.
Pesantren Sebagai Pusat Transformasi Sosial
Dunia pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, memegang peranan vital dalam perjuangan keadilan gender. Pesantren bukan hanya tempat belajar kitab kuning, tetapi juga pusat pembentukan karakter, pemikiran keagamaan, dan budaya sosial. Dalam konteks ini, pesantren memiliki potensi besar untuk mentransformasi cara pandang keagamaan menuju pemahaman Islam yang inklusif dan adil gender.
Di beberapa pesantren, kita mulai melihat inisiatif baru yang menggembirakan. Kurikulum dengan perspektif gender mulai diperkenalkan. Para santri diajak untuk mengkaji ulang ayat-ayat Al-Qur’an tentang perempuan dalam perspektif kontekstual dan adil. Materi tentang tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah Islam juga mulai diajarkan sebagai inspirasi dan pembelajaran.
Lembaga-lembaga seperti Rahima (Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan) dan Fahmina Institute di Cirebon telah bekerja sama dengan berbagai pesantren untuk mengembangkan modul pendidikan gender berbasis Islam. Modul-modul ini dirancang dengan merujuk pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, serta menggunakan metode yang partisipatif dan kontekstual.
Beberapa pesantren yang telah menjadi pelopor dalam pengembangan modul pendidikan gender berbasis Islam antara lain:
- Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Cirebon: Di bawah kepemimpinan Nyai Hj. Masriyah Amva, pesantren ini menjadi salah satu pionir dalam pendidikan gender yang berbasis tafsir keadilan. Mereka aktif menyelenggarakan pelatihan tafsir berbasis kesetaraan gender kepada para santri dan alumni.
- Pondok Pesantren Annuqayah, Madura: Mengembangkan kurikulum kritis yang mengajak santri berdialog tentang isu-isu sosial, termasuk relasi gender, dengan pendekatan Islam progresif.
- Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon: Terlibat aktif dalam program pelatihan dengan Rahima, pesantren ini membuka ruang dialog antar santri dan pengajar mengenai peran perempuan dalam Islam dan masyarakat.
Lebih penting lagi, munculnya ulama perempuan dari lingkungan pesantren menjadi tonggak perubahan yang sangat strategis. Mereka bukan hanya mengisi ruang-ruang pengajian ibu-ibu, tetapi juga tampil sebagai pembicara, penulis, peneliti, dan penggerak perubahan sosial. Beberapa nama penting ulama perempuan pesantren yang menjadi simbol transformasi antara lain:
- Nyai Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin: Akademisi dan aktivis yang memiliki latar belakang pesantren. Ia berperan besar dalam agenda moderasi beragama dan advokasi hak-hak perempuan di forum internasional.
- Nyai Hj. Badriyah Fayumi: Lulusan pesantren dan mantan anggota Komisi VIII DPR RI, serta dikenal aktif dalam forum-forum nasional dan internasional untuk membahas isu perempuan dalam Islam. Beliau juga menjadi tokoh penting dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).
- Nyai Hj. Maria Ulfah Anshor: Pengasuh pesantren sekaligus anggota Komnas Perempuan. Ia juga terlibat dalam pendidikan anti-kekerasan dan literasi keagamaan yang ramah gender di banyak wilayah.
- Nyai Hj. Nur Rofiah: Seorang doktor tafsir lulusan UIN Syarif Hidayatullah dan pengasuh kajian tafsir yang progresif. Melalui platform “Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)”, ia mengedukasi publik, termasuk komunitas pesantren, tentang pentingnya keadilan gender sebagai nilai Islam.
Mereka menjadi wajah Islam yang ramah, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan. Dengan tradisi keilmuan dan otoritas moral yang dimilikinya, para Nyai dan Ulama perempuan ini menjadi jembatan antara tradisi pesantren dan kebutuhan transformasi sosial.
Pesantren hari ini bukan hanya benteng nilai-nilai keislaman klasik, tetapi juga menjadi pusat dialektika sosial dan agama yang sangat penting dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran dan hak perempuan. Ketika pesantren bicara tentang keadilan gender dari dalam tradisi Islam sendiri, maka suara itu akan lebih didengar dan diterima masyarakat luas. Inilah kekuatan kultural yang tak dimiliki lembaga lain.
Dari Pesantren untuk Indonesia yang Lebih Adil Gender
Keadilan gender bukan hanya isu perempuan, tetapi isu umat. Ketika perempuan dipinggirkan, maka potensi umat terpotong setengah. Ketika perempuan diberdayakan, maka seluruh masyarakat ikut tumbuh. Kini saatnya kita bergerak bersama. Pemerintah, akademisi, aktivis, dan tokoh agama perlu bersinergi untuk menciptakan kebijakan, sistem pendidikan, dan ruang publik yang inklusif dan adil gender. Dan di barisan depan, dunia pesantren harus tampil sebagai pelopor.
Pesantren memiliki sumber daya strategis untuk itu—santri, Kyai, Nyai, pengasuh, ustadz, ustadzah, serta jaringan alumni yang luas. Dengan mendorong kurikulum yang membebaskan, penguatan ulama perempuan, dan literasi keagamaan yang progresif, pesantren bisa mencetak generasi pemimpin yang visioner dan berpihak pada keadilan. Kita butuh narasi baru: bahwa perempuan cerdas bukan ancaman, bahwa menuntut keadilan bukan pembangkangan, dan bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan adalah bagian dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar.
Dari pesantren, kita bisa memulai perubahan itu. Dari pesantren, kita bisa merumuskan ulang Islam yang lebih membebaskan. Dari pesantren, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil untuk semua.
Tag:iat, keadilangender, pesantren, unkafa, ushuluddin
You may also like
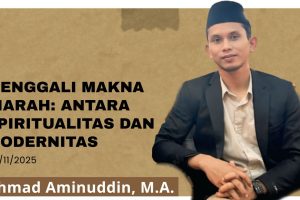
Menggali Makna Ziarah: Antara Spiritualitas dan Modernitas